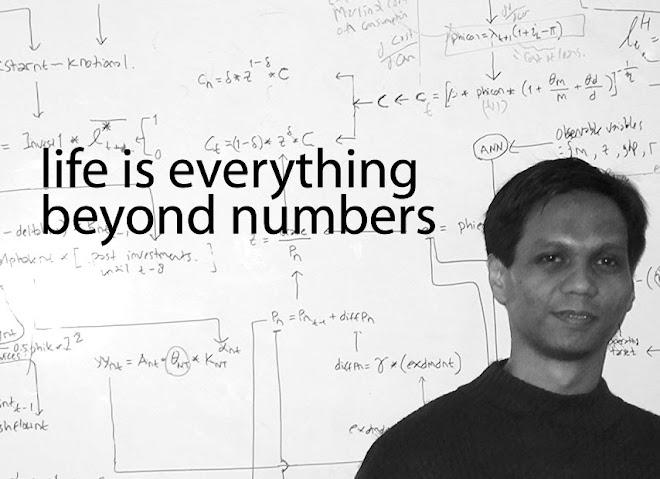Note: Maaf jika ada kata dan tulisan yang dianggap tidak sopan. Sama sekali tidak bermaksud untuk melanggar batas etika, namun biarlah semua tahu bahwa kenyataan kekejaman yang mereka alami memang sangat jauh melebihi batas-batas kemanusiaan...
Ibu Rusminah, 68 tahun, sekarang usaha warung sembako diGurah-Kediri
Nduk, biarlah Ibu hidup di sini di desa Gurah yang kecil ini. Beristirahat dalam kedamaian, yang akhirnya Ibu temukan disini, di tanah kelahiran Ibumu ini. Hingga akhir waktu nanti. Terlalu banyak letih dan telah kering airmata untuk menangisi kisah gelap kehidupan Ibu. Dan biarlah itu menjadi milik Ibu sendiri. Sementara kamu, Nduk..hiduplah dengan bahagia. Duniamu masih luas terbentang..sementara dunia Ibu..ah Ibu ndak pingin kamu tahu…
“Iki kabeh kanggo mulyake uripmu, Nduk..”, begitu simbah puterimu waktu itu menasehati Ibu untuk pasrah nrimo perjodohan dengan Bapakmu. Ibumu cuma guru sekolah rakyat, ndak tau apa-apa soal peristiwa-peristiwa besar kecuali hanya ingin ikut mendidik dan menjadikan anak-anak desa menjadi lebih pintar. Bapakmu memang aktif dalam organisasi untuk membela rakyat kecil. Ia pergi kesana-kemari entah kemana, karena ia memang ndak mau melibatkan Ibu dalam urusan pekerjaan laki-laki.
Tiba-tiba dunia Ibu berubah gelap pada suatu hari itu, satu oktober tahun enam puluh
Dan ketika seorang Perwira dari mereka datang kepada Ibu, mengeluarkan Ibu dari neraka itu, sejenak Ibu memiliki harapan akan kehidupan. Ibu dbawanya ke rumah dinasnya, diberi baju dan diberi makan. Tapi, Nduk…sama saja ia! Ibu bukanlah manusia bebas, tapi tahanan rumah dengan status pembantu rumah tangga sekaligus pemuas nafsu perwira itu bertahun-tahun lamanya! Ibu ndak boleh keluar rumah..atau akan dikembalikan ke neraka. Ibu ndak pernah dikawin, meskipun kamu terlahir di rumah itu. Baginya, Ibu cuma perabot rumah tangga yang digunakan jika perlu, untuk kemudian dibuang setelah bosan. Ia begitu saja pergi ke
Saat itulah Ibu kembali ke sini, ke desa kecil tanah kelahiran ini, menitipkanmu ke simbah kakung dan putri dan kemudian diangkat anak oleh Ibu Lasmi, pemilik Konveksi tempat Ibu bekerja. Dan Ibu bersyukur, karena kamu akhirnya bisa jalani hidupmu dengan lebih baik…lulus SMA..lulus jadi sarjana..kerja di bank…dan berkeluarga sekarang. Hidupmu terbentang, Nduk. Raihlah itu. Biarlah Ibu di sini saja, di
Ibu Yanti, 57 tahun, sekarang berjualan sayur dan buah di
Anak-anakku, Ibu hanya mempunyai satu keinginan sebelum Ibu mati. Yaitu..bertemu keluarga almarhum jenderal-jenderal itu. Ibu mau menceritakan kepada mereka, bahwa Ibu bukan pembunuh jenderal apalagi penyayat-nyayat penis mereka..
Ibu baru berumur 14 tahun, sekolah SMP, waktu tentara-tentara itu menangkap Ibu. Saat itu jiwa muda Ibu sedang bersemangat karena terbakar api “Ganyang
Ibu dan semua perempuan hari itu dikumpulkan di lapangan, disuruh telanjang tanpa sehelai pakaianpun bahkan tanpa celana dalam. Melawan berarti pukulan popor senapan dan siksaan. Dari pagi sampai petang Ibu berdiri di lapangan, telanjang..tanpa diberi minum apalagi makan..dan terus begitu selama dua hari dua malam. Tentara-tentara itu terus berteriak-teriak, “Ini wajah telanjang perempuan-perempuan komunis! Dasar sundal! Kamu dilatih PKI disini untuk membunuh dan menyayat-nyayat tubuh
Disela-sela teriakan mereka, setan-setan berseragam itu megucap-usapkan ujung senjata mereka ke payudara kami, atau merudnuk dan meremas-remaskan tangan mereka, atau menusuk-nusukkan ujung aras senjata ke kemaluan kami. Bagi mereka, kami hanyalah tontonan dan obyek tertawaan menarik yang bisa menaikkan hasrat binatang mereka. Pada hari ketiga, dunia Ibu semakin gelap anakku…kami semua digiring ke barak kosong. Katanya untuk diinterogasi,tapi yang terjadi adalah penganiayaan fisik secara lebih biadab lagi. Siapa sebenarnya mereka?! Manusia atau bukan?! Mereka menyundutkan api rokok ke payudara-payudara kami, membakar rambut kemaluan, memperkosa kami secara beramai-ramai dan merusak organ seksual kami dengan benda-benda..leher botol, tongkat pemukul, kemoceng, laras senjata dan banyak lagi benda yang menumpahkan darah kami. Seperti kesetanan, mereka menyetrum jari-jari, puting-puting payudara dan klitoris kami. Terus dan terus, hingga Ibu berulangkali pingsan. “Habisi saja! Habisi!”, teriak mereka. Dan Ibu sudah hancur. Ibu menyerah.
Hanya “ya” yang boleh Ibu jawab ketika beberapa wartawan dipertemukan dengan kami. Mereka bertanya macam-macam seputar sebuah peristiwa besar tewasnya jenderal-jenderal. Dan Ibu hanya boleh menjawab “ya”…atau tiga orang algojo yang sudah berkali-kali memeriksa dan memerkosa Ibu akan menyiksa Ibu lebih kejam lagi katanya. Ramai-ramai wartawan bertanya: apakah benar Ibu ikut menyiksa jenderak-jenderal? Apakah Ibu ikut menari-narkan tarian “Harum Bunga” sambil telanjang di depan para jenderal? Apa benar Ibu dan kawan-kawan ini sukwati yang berpesta seks di depan para jenderal? Dan untuk semua hal yang Ibu tidak pernah lakukan…tapi Ibu hanya bleh manjwab “ya” dan “ya” dan “ya” saja…. Dan hadiah dari kepatuhan Ibu adalah…Ibu diperkosa berkali-kali lagi oleh seorang interogator! Mereka manusia atau bukan, Nak ?!!.Siapa mereka?!..
Ibu Darmi, 78 tahun, membuka warung di
Anak,..jangan suruh Ibumu ini menari lagi. Jangan minta Ibumu tuk mendengarkan lagi gamelan. Karena batin ini menjadi menjerit sekeras-kerasnya. Karena pada setiap dentingnya membawa kembali kisah gelap. Dan pada setiap lekuk geraknya dibasahi air mata dan darah.
Seandainya anak tahu, sesungguhnya darah Ibumu adalah darah seorang penari. Dan ruh jiwa Ibu adalah ruhnya penari. Ibumu ini sampai menari di istana di hadapan Presiden Sukarno. Yang Ibu tahu, bahwa Tuhan menganugerahkan keindahan gerak untuk Ibumu ini, yang melaluinya Ibu temukan bahagia. Ibu tahu, bahwa Bapakmu sangat aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Tapi Ibu tak pernah punya ketertarikan untuk itu, dan Bapakmu memang tak membolehkan Ibu untuk ikut berorganisasi. Ibu hanya boleh menari, karena disitulah bahagianya Ibu…
Tapi jiwa dan daya hidup Ibu kemudian direnggut paksa pada suatu hari di penghujung bulan oktober tahun enam puluh
Anak, wajah-wajah mereka menjelma siluman dan leak. Pakaian Ibumu mereka renggut dan sobek dan Ibu diarak berjalan kaki keliling desa. Di leher Ibu, mereka gantungkan tulisan besar “Aku Lonte PKI” dan di punggung “Aku Dajal! Pembunuh Jenderal!”. Ibu tidak tahu apa maksud mereka? Siapa itu jenderal-jenderal yang mereka maksudkan? Yang Ibu tahu cuma menari…
Tapi mereka sudah menjelma buta. Ibu diikat di depan balai desa, dan bayak laki-laki menggerayangi seluruh lekuk dan lindap-lindap tubuh Ibu. Sehari semala penuh, tanpa minum dan tanpa makan. Telanjang. Hari berikutnya Ibu digiring ke pos tentara. Disana tak berbeda yang Ibu jumpai. Ibu diinterogasi tanpa henti selama dua hari, dan selama itu juga Ibumu disuruh menari di atas meja interogasi dengan telanjang bulat. Dan siluman leak berseragam itu menggerayangi bagian –bagian tubuh Ibu dengan semau-mau mereka. Duh Anak,…perlakuan mereka sangat durjana! Untunglah kemudian Ibu dibebaskan karena mereka tidak bisa membuktikan keterlibatan Ibu dengan PKI maupun ormas2nya. Ibumu cuma penari. Tapi Ibu tetap wajib lapor setiap bulannya.
Duh Anak,..derita belum sirna ternyata! Setiap kali lapor ke kantor tentara, terus saja Ibu dipaksa untuk melayani nafsu binatang para pembesar tentara di kantor mereka. Terkadang Ibu dibawa ke tempat-tempat dan diperkosa, terkadang mereka datang bergiliran ke rumah Ibu untuk menagih setoran buat nafsu leaknya. Mereka datang dan pergi. Tidak peduli siang atau malam hari. Kalo Ibu menolak, mereka mengancam akan menuduh Ibu sebagai eks-Tapol yang melarikan diri.
Anak, Ibu tak boleh lagi masuk ke Pura. Karena bagi mereka Ibu adalah seorang pelacur dan eks-tapol komunis. Ndak ada seorangpun yang mau membela Ibumu ini. Ibu terasing, terkucil, dijauhi dan dibenci, Duh, Anak..betapa manusia itu sangat mudah menjadi siluman pembenci dan perusak yang berkedok “kebenaran” dan “kesucian”. Bahkan keluarga Ibu sendiri sudah menghapus nama Ibu dari silsilah keluarga. Alangkah dahsyatnya peristiwa besar di akhir september enam puluh
Sejak saat itu, Ibumu tak pernah lagi menari. Meski bagi Ibu menari adalah gerakan jiwa dan daya hidup..namun sejak peristiwa itu menari telah menjadi mimpi terburuk dalam kehidupan Ibu. Tak bisa lagi Ibu mendengar gamelan. Tak sanggup lagi Ibu menari. Anak, Ibumu sekarang ini tinggal sebatang jasad. Tanpa jiwa-raga, tubuh dan ruh yang penari. Inilah beban yang harus Ibu pikul, mungkin sampai nafas ini berhenti…
Dedicated to mothers who've been living in the darkside of this life. May God bless you all, Ibu...
Disarikan dibahasakan kembali dari tuturan lisan langsung para korban yang dirangkum dalam buku “Suara Perempuan Korban Tragedi ‘65” by Ita F.Nadia, Galang Press, 2008.
..