
Mereka yang tlah melihat dunia, terbukalah wawasannya. Di hadapannya terbentang kemungkinan-kemungkinan, dan ia kini berani untuk memiliki impian. Ia kini bisa menatap gemintang di langit yang benderang, yang tak pernah bisa ia saksikan di langit negerinya yang selama ratusan tahun hanya gelungan mendung mengkungkung. Ia kini adalah anak semua bangsa, yang bisa menjadi sama majunya dan bisa sama beradabnya dengan bangsa-bangsa lain di dunia! Mereka pun menyeru kepada saudara-saudara mereka setanah air di Hindia Belanda. Untuk mengikuti jejak langkah mereka.
“Hai kalian, putra-putra Jawa, demi kalian disini aku memberanikan diri berseru. Dengarkanlah, lonceng telah berbunyi agar kalian bangun dari tidur yang membiuskan, untuk membela hak-hak kalian, yaitu hak untuk berlomba-lomba dengan mereka yang lebih beradab dan berkembang dalam ilmu, kecerdasan dan ketekunan, hingga kalian menjadi berkah bagi tanah air kalian sendiri!..kembangkan seluruh kekuatan kalian untuk membantu rakyat kita membentuk diri, dari kanak-kanak sampai dewasa.”
“Hai kalian, putra-putra Jawa, demi kalian disini aku memberanikan diri berseru. Dengarkanlah, lonceng telah berbunyi agar kalian bangun dari tidur yang membiuskan, untuk membela hak-hak kalian, yaitu hak untuk berlomba-lomba dengan mereka yang lebih beradab dan berkembang dalam ilmu, kecerdasan dan ketekunan, hingga kalian menjadi berkah bagi tanah air kalian sendiri!..kembangkan seluruh kekuatan kalian untuk membantu rakyat kita membentuk diri, dari kanak-kanak sampai dewasa.”
Demikianlah seruan Sosrokartono, salah seorang pelajar perintis di negeri Belanda dan penyeru pertama (yang juga adalah kakak kandung dari RA Kartini) pada pertengahan tahun 1899. Seruan senada disampaikan pula melalui media cetak yang dibuat dan disebarluaskan ke Hindia Belanda oleh beberapa bumiputera yang telah menetap di negeri Belanda. Abdul Rivai, seorang wartawan dan dokter asal Sumatera Barat, menerbitkan koran Pewarta Wolanda (1899) dan kemudian Bandera Wolanda (1901) bersama-sama dengan Sosrokartono dan Abdullah (putra Dr.Wahidin Soedirohoesodo). Koran Kolonial Weekblad (1901) dan Bintang Hindia (1902) kemudian menyusul dengan membawa pesan-pesan yang sama.
Memasuki tahun pertama dari abad keduapuluh, mulailah berdatangan putera-putera pribumi ke negeri Belanda menjawab seruan itu. Sejalan dengan dimulainya pula kebijakan “politik etis” oleh pemerintah kolonial terhadap negeri-negeri jajahannya, maka kesempatan untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan negeri Belanda semakin dibuka. Sebuah kebijakan untuk mendekatkan dan mempererat hubungan persaudaraan antara negeri jajahan dengan negeri penjajahnya lewat jalan budaya dan bahasa. Maka berdatanganlah mereka ke negeri Belanda: putera-putera raja nusantara, putera Sultan Kutai, putera Sultan Asahan, putra kaum bangsawan Jawa, anak Bupati Magelang, anak Susuhunan Solo, dan orang-orang biasa.
Bahkan R.A.Kartini melihat bahwa pergi ke Belanda adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan dan (lebih penting lagi) kebebasan dirinya, “Cakrawalaku pasti akan lebih luas, jiwaku pasti akan lebih kaya, dan semua itu tak sangsi lagi pasti akan berpengaruh baik baik bagi pelaksanaan tugasku…Negeri Belanda harus dan pasti menjadikan diriku benar-benar seorang perempuan merdeka.”
Bagi para penyeru pertama, satu-satunya jalan yang mereka lihat untuk menggapai masa depan yang lebih benderang hanyalah dengan menerima kondisi keterjajahan ini sebagai sebuah “takdir” yang tidak dapat diubah lagi. Berbagai upaya untuk merubah takdir telah pupus ditumpas, di Jawa, di Aceh, di Sumatera, di timur kepulauan nusantara. Dan kerajaan penjajah tetap berdiri tegak tak terkalahkan. Tak ada siapa yang bisa merubah kondisi ini, karena memang inilah takdir hidup kita. Dan yang bisa kita lakukan kini adalah mencoba “mengambil hikmah” dan manfaat dari keterjajahan ini. Yang bisa kita lakukan, dalam pemikiran mereka, adalah setidaknya mengharap simpati dan niat baik (dan rasa kasihan) dari Sang Ratu Belanda terhadap Hindia Belanda…untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang sesungguhnya. Yang dengannya kita diberinya kesempatan untuk mencicipi kesejahteraan dan kemajuan sebagaimana anak-anaknya di negeri Belanda. Dan sebagai imbalannya, akan kita berikan kesetiaan kita kepada Yang Mulia berupa ketaklukan di bawah satu Ratu dan satu bendera: Kemaharajaan Belanda.
Maka pada penerbitan pertama koran Bintang Hindia (1902), sang redaktur menjelaskan, bahwa “Kami ingin banyak bercerita kepada sesama warga negara Pribumi dan warga negara Timur lainnya tentang Ibu Pertiwi di Eropa, dan dengan itu membangkitkan minat mereka pada berbagai hal, yang sampai waktu itu berada di luar lingkungan pemikiran mereka…….Kami ingin memperkokoh kesetiaan kepada Bendera dan Ratu, namun kesetiaan yang tidak didasarkan pada rasa takut yang bodoh dan pengecut, melainkan didasarkan pada keyakinan yang benar, pada rasa cinta.”
Maka dituliskan pada Kop surat kabar Bandera Wolanda (1901) maupun Bintang Hindia (1902), “Kekallah karadja an Wolanda Masjhoerlah tanah Hindia” di kirinya. Dan di kanannya dituliskan “Sampai mati satya kepada Sri Baginda Maharadja”.
Memasuki tahun pertama dari abad keduapuluh, mulailah berdatangan putera-putera pribumi ke negeri Belanda menjawab seruan itu. Sejalan dengan dimulainya pula kebijakan “politik etis” oleh pemerintah kolonial terhadap negeri-negeri jajahannya, maka kesempatan untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan negeri Belanda semakin dibuka. Sebuah kebijakan untuk mendekatkan dan mempererat hubungan persaudaraan antara negeri jajahan dengan negeri penjajahnya lewat jalan budaya dan bahasa. Maka berdatanganlah mereka ke negeri Belanda: putera-putera raja nusantara, putera Sultan Kutai, putera Sultan Asahan, putra kaum bangsawan Jawa, anak Bupati Magelang, anak Susuhunan Solo, dan orang-orang biasa.
Bahkan R.A.Kartini melihat bahwa pergi ke Belanda adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan dan (lebih penting lagi) kebebasan dirinya, “Cakrawalaku pasti akan lebih luas, jiwaku pasti akan lebih kaya, dan semua itu tak sangsi lagi pasti akan berpengaruh baik baik bagi pelaksanaan tugasku…Negeri Belanda harus dan pasti menjadikan diriku benar-benar seorang perempuan merdeka.”
Bagi para penyeru pertama, satu-satunya jalan yang mereka lihat untuk menggapai masa depan yang lebih benderang hanyalah dengan menerima kondisi keterjajahan ini sebagai sebuah “takdir” yang tidak dapat diubah lagi. Berbagai upaya untuk merubah takdir telah pupus ditumpas, di Jawa, di Aceh, di Sumatera, di timur kepulauan nusantara. Dan kerajaan penjajah tetap berdiri tegak tak terkalahkan. Tak ada siapa yang bisa merubah kondisi ini, karena memang inilah takdir hidup kita. Dan yang bisa kita lakukan kini adalah mencoba “mengambil hikmah” dan manfaat dari keterjajahan ini. Yang bisa kita lakukan, dalam pemikiran mereka, adalah setidaknya mengharap simpati dan niat baik (dan rasa kasihan) dari Sang Ratu Belanda terhadap Hindia Belanda…untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang sesungguhnya. Yang dengannya kita diberinya kesempatan untuk mencicipi kesejahteraan dan kemajuan sebagaimana anak-anaknya di negeri Belanda. Dan sebagai imbalannya, akan kita berikan kesetiaan kita kepada Yang Mulia berupa ketaklukan di bawah satu Ratu dan satu bendera: Kemaharajaan Belanda.
Maka pada penerbitan pertama koran Bintang Hindia (1902), sang redaktur menjelaskan, bahwa “Kami ingin banyak bercerita kepada sesama warga negara Pribumi dan warga negara Timur lainnya tentang Ibu Pertiwi di Eropa, dan dengan itu membangkitkan minat mereka pada berbagai hal, yang sampai waktu itu berada di luar lingkungan pemikiran mereka…….Kami ingin memperkokoh kesetiaan kepada Bendera dan Ratu, namun kesetiaan yang tidak didasarkan pada rasa takut yang bodoh dan pengecut, melainkan didasarkan pada keyakinan yang benar, pada rasa cinta.”
Maka dituliskan pada Kop surat kabar Bandera Wolanda (1901) maupun Bintang Hindia (1902), “Kekallah karadja an Wolanda Masjhoerlah tanah Hindia” di kirinya. Dan di kanannya dituliskan “Sampai mati satya kepada Sri Baginda Maharadja”.
Disarikan dan dibahasakan kembali dari buku “Di Negeri Jajahan: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950”, Harry A.Poeze, KITLV Jakarta dan KPG, Juli 2008.
..

























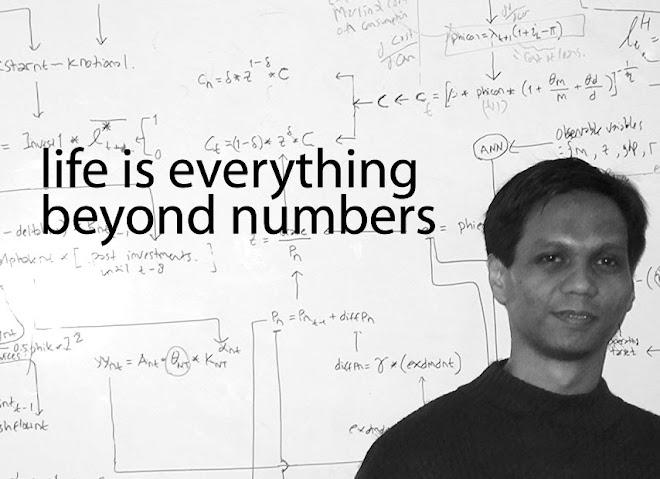
Tidak ada komentar:
Posting Komentar