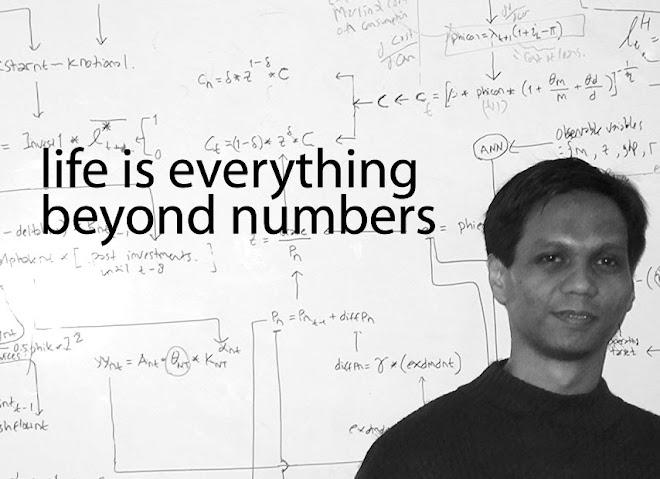Apakah di balik segala wujud dan fenomena? Apa (atau siapa) yang menjadikan ada? Dari manakah ada? Sebelum semua wujud, apakah yang ada? Anaxagoras (500SM-428 SM), sang filsuf awal dari Klazomenae-Yunani mencoba menguraikan. Tidaklah mungkin bahwa yang ada itu menjadi tidak ada. Materi tidak pernah terjadi dan tidak akan musnah. Karena materi adalah abadi sejak dulu hingga selamanya. “Terjadi”nya sesuatu tak lain daripada pencampuran homiomeira, benih-benih realitas dari benda. Sementara “musnah”nya sesuatu adalah pemisahan benih-benih itu satu sama lain menjadi unsur-unsur pembentuknya. Namun pemisahan tidak bisa mengurangi totalitas, melainkan segalanya selalu tetap sama.
Tapi apakah yang menyebabkan pencampuran dan pemisahan materi itu? Apakah yang menggerakkan prosesnya? Anaxagoras menjelaskan, bahwa di balik proses-proses material itu ada sesuatu sebagai “yang menggerakkan”: Nous (roh, mind).
Nous memiliki eksistensi sendiri, tak tercampur dengan yang lainnya, mandiri dan mengetahui segala sesuatu. Ia adalah materi yang terhalus dan termurni, hadir di mana-mana dan menguasai segala yang kecil maupun yang besar. Nous merupakan asas rohani yang logis sekaligus dinamis yang melekat pada roh, pikiran dan kehendak manusia.
Nous adalah asal-usul gerakan dalam alam semesta dan penata segala sesuatu di dalamnya. Segalanya adalah satu pada awalnya, dalam kesatuan yang tak jelas dan tak memiliki karakter. Tak ada warna, tak ada lembab, kering, panas, dingin, terang maupun gelap. Hanya benih-benih realitas yang tak terhingga jumlahnya yang membawa di dalam dirinya semua bentuk, warna, dan sifat benda-benda. Kemudian Nous menggerakkan kesatuan elemen ini dalam sebuah putaran (rotation) kecil di awalnya, yang kemudian semakin membesar dan membesar. Maka segala sesuatu mengalami pencampuran dan pemisahan. Yang bercampur dan yang terpisah semuanya dalam pengetahuan Nous, yang menata segala sesuatu yang belum menjadi maupun yang tidak menjadi, yang dulu maupun kini. Nous adalah kekuatan penata, sumber keteraturan dan keindahan.
Tetapi segala sesuatu dalam alam semesta tak pernah terpisah total dari segala sesuatu lainnya. Di dalam segala sesuatu terkandung pula segala sesuatu. Dan Nous, sejak kekal hingga selamanya berada dalam segala yang terpisah maupun yang tercampur itu.
..
Jumat
Rabu
Manunggaling Kawulo Gusti roso Londo
Dalam refleksinya tentang dasar akhir dari segenap kenyataan yang ada, Spinoza (1632-1677) seorang filsuf Rasionalis Belanda, merumuskan konsep substansi sebagai hakikat dari segala eksistensi. Ia melihat bahwa di balik beragam wujud benda-benda jasmaniah maupun bentuk-bentuk ruhaniah (pemikiran, perasaan), hakikatnya hanya terdapat satu substansi. Substansi tersebut merupakan sebuah kenyataan yang mandiri, yang ada pada dirinya sendiri dan dipahami melalui dirinya sendiri. Ia terisolasi dari kenyataan yang lain, sama sekali tidak tergantung kepada yang lain, dan tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain (causa sui). Sifat substansi tersebut adalah abadi, tidak terbatas, mutlak dan tunggal/individual.
Bagi Spinoza, hanya ada satu yang bisa memenuhi semua definisi tersebut, yaitu Allah. Dan karena Allah adalah satu-satunya substansi, maka keberadaan semua yang ada dalam alam semesta ini –jasmaniah maupun ruhaniah—hakikatnya adalah berasal dari Allah dan tergantung sepenuhnya kepada Allah. Beragam “individualitas” yang nampak dari benda-benda, aliran pemikiran, imajinasi dan sebagainya, sesungguhnya hanyalah merupakan modus (cara penampakan) dari Allah sebagai substansi satu-satunya. Lebih lanjut Spinoza mengatakan, bahwa “ada”-nya wujud segala sesuatu pun sejatinya hanyalah merupakan atribute dari Allah (persepsi intelek tentang representasi sifat hakiki) : badan/keluasan adalah atribute Allah (Deus est res extensa) dan jiwa/pemikiran sejatinya adalah juga atribute Ilahi (deus est res cogitans).
Dalam cara pandang demikian, maka Spinoza menyimpulkan bahwa segenap wujud serta kenyataan dalam alam semesta hakikatnya adalah Allah! Alam dan Allah adalah dua hal yang identik dan kenyataan yang tunggal: Deus Sive Natura (Allah atau Alam). Perbedaan antara Allah dan alam sesungguhnya hanyalah soal istilah atau sudut pandang semata. Sebagai Allah, alam adalah natura naturans (alam yang melahirkan) yaitu sisi aktif/produktif dari alam. Sebagai dirinya sendiri, alam adalah natura naturata (alam yang dilahirkan) yaitu sisi pasif dari alam sebagai hasil tindakan sisi aktif. Tetapi hakikat substansinya adalah tunggal dan sama. Dari sudut pandang manusia, semesta dunia dilihatnya ada di dalam Allah dengan dua atribute-Nya (keluasan dan pemikiran). Maka ketika kita memandang dunia melalui atribute jiwa/pemikiran, kita menyebutnya sebagai “Allah”. Sementara itu, jika kita memandang dunia melalui atribute badan/keluasan, maka kita menyebutnya sebagai “alam”. Tetapi sekali lagi hakikat substansinya tetaplah tunggal dan sama: Deus Sive Natura.
..
Bagi Spinoza, hanya ada satu yang bisa memenuhi semua definisi tersebut, yaitu Allah. Dan karena Allah adalah satu-satunya substansi, maka keberadaan semua yang ada dalam alam semesta ini –jasmaniah maupun ruhaniah—hakikatnya adalah berasal dari Allah dan tergantung sepenuhnya kepada Allah. Beragam “individualitas” yang nampak dari benda-benda, aliran pemikiran, imajinasi dan sebagainya, sesungguhnya hanyalah merupakan modus (cara penampakan) dari Allah sebagai substansi satu-satunya. Lebih lanjut Spinoza mengatakan, bahwa “ada”-nya wujud segala sesuatu pun sejatinya hanyalah merupakan atribute dari Allah (persepsi intelek tentang representasi sifat hakiki) : badan/keluasan adalah atribute Allah (Deus est res extensa) dan jiwa/pemikiran sejatinya adalah juga atribute Ilahi (deus est res cogitans).
Dalam cara pandang demikian, maka Spinoza menyimpulkan bahwa segenap wujud serta kenyataan dalam alam semesta hakikatnya adalah Allah! Alam dan Allah adalah dua hal yang identik dan kenyataan yang tunggal: Deus Sive Natura (Allah atau Alam). Perbedaan antara Allah dan alam sesungguhnya hanyalah soal istilah atau sudut pandang semata. Sebagai Allah, alam adalah natura naturans (alam yang melahirkan) yaitu sisi aktif/produktif dari alam. Sebagai dirinya sendiri, alam adalah natura naturata (alam yang dilahirkan) yaitu sisi pasif dari alam sebagai hasil tindakan sisi aktif. Tetapi hakikat substansinya adalah tunggal dan sama. Dari sudut pandang manusia, semesta dunia dilihatnya ada di dalam Allah dengan dua atribute-Nya (keluasan dan pemikiran). Maka ketika kita memandang dunia melalui atribute jiwa/pemikiran, kita menyebutnya sebagai “Allah”. Sementara itu, jika kita memandang dunia melalui atribute badan/keluasan, maka kita menyebutnya sebagai “alam”. Tetapi sekali lagi hakikat substansinya tetaplah tunggal dan sama: Deus Sive Natura.
..
Minggu
"Kebenaran Instan" Agama-Agama Langitan
Lintasan pencarian kedamaian hati adalah sebanyak jumlah jiwa-jiwa. Setiap orang memiliki prosesinya sendiri-sendiri, melalui kelokan dan tanjakannya sendiri, memunguti serpihan demi serpihan makna di sepanjang perjalanan yang dilalui. Ruhaninya bertumbuh dari semula kuncup menjadi berkembang indah disirami air pengetahuan dan hembusan angin pemahaman akan makna-makna kehidupan. Dalam terminologi GW Friedrich Hegel (1770-1831), sang raksasa filsafat modern, verstand (akal budi) dan vernunft (intelek) harus mengembara untuk menyingkap kebenaran di balik segala fenomena. Untuk mendapatkan kebenaran sejati, ia harus mengembara dan mendewasakan dirinya..dari ruh individual menjadi ruh obyektif dan akhirnya menyentuh ruh absolut!..
Seringkali perjalanan itu memakan waktu berpuluh-puluh tahun bahkan sepanjang hidupnya. De Geist (kesadaran akan esensi), sebagai ruh pengembara yang telah dewasa, kemudian mentajalikan dirinya ke dalam virtues dan wisdoms....yang selanjutnya dibawa melintasi masa dan diwariskan dari generasi ke generasi. Demikianlah "agama-agama bumi" mengkristalisasi prosesi pencariannya secara bersahaja...
Tidak demikian dengan "agama-agama langit", yang menerima seperangkat kebenaran begitu saja jatuh dari dunia atas sana. Sementara agama-agama bumi pelan sekali melangkah memunguti remah-remah hikmah, agama-agama langit menikmati previlege yang sangat besar..."ketiban kebenaran" dalam semalam atau beberapa tahun saja... :)
Boleh saja kita tidak meragukan kematangan De Geist dari para Nabi dan Rasul yang menerima anugerah tersebut. Persentuhan Nabi dan Rasul dengan Yang Maha Mengetahui Semuanya, tentu saja harus diawali dengan penyiapan Nabi dan Rasul sebagai "wadah" yang harus mampu menampung THE ultimate wisdoms dan esensi dari segala kenyataan kehidupan di masa lalu , masa kini, dan masa datang seluruhnya. Seluruh prosesi dan perjalanan makhluk dalam mencari kebenaran telah berkumpul dan terangkum di dalam wawasan pengetahuannya. Demikian pula dengan para ulil albab (mereka yang inti nuraninya -lubb- telah tercerahkan. Jadi bukan sekedar "orang yang punya ilmu", penghafal buku atau sekedar "ulama") sebagai para pewaris Nabi dan Rasul.
Namun dari keluasan pengetahuan itulah, justru kemudian Nabi Rasul dan para ulil-albab tampil dalam kelembutan, bersahaja, memahami, toleran dan berempati di hadapan mereka yang lain yang berbeda. Pengetahuan mereka telah melingkupi pengetahuan para pencari, dan justru karena itu para Nabi Rasul dan mereka yang tercerahkan tampil penuh kasih sayang, rendah hati, mengasuh dan menunjukkan jalan kelembutan kepada mereka yang masih berjalan mencari. Semakin berisi, semakin merunduk sang padi...
Tanpa keluasan pengetahuan dan empati akan prosesi pencarian individu jiwa-jiwa, yang bisa mengambil jalan-jalan yang beragam dan berbeda-beda satu sama lain, para pengamal "kebenaran instan" agama-agama langit hanya akan tampil penuh arogansi, merendahkan, memaksakan....dan cenderung menutup mata dari keindahan kristal-kristal penuh hikmah yang tumbuh dari agama-agama bumi. Tanpa kematangan de Geist, para pengamal "kebenaran instan" agama langit hanya akan mentok pada deretan fenomena inderawi tanpa mampu melampauinya tuk melihat makna yang lebih dalam di baliknya. Tanpa "wadah" yang memadai, "kebenaran instan" agama langit tak mampu dicicipi secara lebih kaya rasa karena pengamalnya lebih sibuk mencekoki sambil berteriak-teriak bak menjual kecap nomer satu...daripada duduk tenang mencicipi sendiri dan menghayati kelembutan citarasanya yang lebih dalam. Dan tanpa keterbukaan, empati serta kelapangan hati, "kebenaran instan" agama- agama langit cuma akan menjadi kumpulan teks yang (seakan) gagap, tuli dan bisu terhadap perkembangan zaman. Yang beku dan tak mau mendengarkan.
Tentu saja bukan berarti teks-nya yang salah, apalagi jika kita meyakini bahwa itu adalah Kalam Ilahi Yang Maha Benar. Tetapi lebih sering karena mereka yang membacanya (dan yang mengaku pandai membacanya) terlalu terlenakan oleh "kebenaran instan" yang dirasa tak perlu lagi dipertanyakan atau diperdebatkan. Prosesi telah selesai, kebenaran telah menjadi. Tak diperlukan lagi perjalanan memunguti remah-remah hikmah dilakukan. Dan dengan begitu...merekapun menjadi buta, tuli dan bisu akan esensi dari luasnya hikmah dan indahnya kristal mutiara yang bertaburan di balik deretan huruf dan kata-kata !
Mereka tak lebih baik dari para penyembah api...
Medistra, Nisfu Sya'ban
..
Seringkali perjalanan itu memakan waktu berpuluh-puluh tahun bahkan sepanjang hidupnya. De Geist (kesadaran akan esensi), sebagai ruh pengembara yang telah dewasa, kemudian mentajalikan dirinya ke dalam virtues dan wisdoms....yang selanjutnya dibawa melintasi masa dan diwariskan dari generasi ke generasi. Demikianlah "agama-agama bumi" mengkristalisasi prosesi pencariannya secara bersahaja...
Tidak demikian dengan "agama-agama langit", yang menerima seperangkat kebenaran begitu saja jatuh dari dunia atas sana. Sementara agama-agama bumi pelan sekali melangkah memunguti remah-remah hikmah, agama-agama langit menikmati previlege yang sangat besar..."ketiban kebenaran" dalam semalam atau beberapa tahun saja... :)
Boleh saja kita tidak meragukan kematangan De Geist dari para Nabi dan Rasul yang menerima anugerah tersebut. Persentuhan Nabi dan Rasul dengan Yang Maha Mengetahui Semuanya, tentu saja harus diawali dengan penyiapan Nabi dan Rasul sebagai "wadah" yang harus mampu menampung THE ultimate wisdoms dan esensi dari segala kenyataan kehidupan di masa lalu , masa kini, dan masa datang seluruhnya. Seluruh prosesi dan perjalanan makhluk dalam mencari kebenaran telah berkumpul dan terangkum di dalam wawasan pengetahuannya. Demikian pula dengan para ulil albab (mereka yang inti nuraninya -lubb- telah tercerahkan. Jadi bukan sekedar "orang yang punya ilmu", penghafal buku atau sekedar "ulama") sebagai para pewaris Nabi dan Rasul.
Namun dari keluasan pengetahuan itulah, justru kemudian Nabi Rasul dan para ulil-albab tampil dalam kelembutan, bersahaja, memahami, toleran dan berempati di hadapan mereka yang lain yang berbeda. Pengetahuan mereka telah melingkupi pengetahuan para pencari, dan justru karena itu para Nabi Rasul dan mereka yang tercerahkan tampil penuh kasih sayang, rendah hati, mengasuh dan menunjukkan jalan kelembutan kepada mereka yang masih berjalan mencari. Semakin berisi, semakin merunduk sang padi...
Tanpa keluasan pengetahuan dan empati akan prosesi pencarian individu jiwa-jiwa, yang bisa mengambil jalan-jalan yang beragam dan berbeda-beda satu sama lain, para pengamal "kebenaran instan" agama-agama langit hanya akan tampil penuh arogansi, merendahkan, memaksakan....dan cenderung menutup mata dari keindahan kristal-kristal penuh hikmah yang tumbuh dari agama-agama bumi. Tanpa kematangan de Geist, para pengamal "kebenaran instan" agama langit hanya akan mentok pada deretan fenomena inderawi tanpa mampu melampauinya tuk melihat makna yang lebih dalam di baliknya. Tanpa "wadah" yang memadai, "kebenaran instan" agama langit tak mampu dicicipi secara lebih kaya rasa karena pengamalnya lebih sibuk mencekoki sambil berteriak-teriak bak menjual kecap nomer satu...daripada duduk tenang mencicipi sendiri dan menghayati kelembutan citarasanya yang lebih dalam. Dan tanpa keterbukaan, empati serta kelapangan hati, "kebenaran instan" agama- agama langit cuma akan menjadi kumpulan teks yang (seakan) gagap, tuli dan bisu terhadap perkembangan zaman. Yang beku dan tak mau mendengarkan.
Tentu saja bukan berarti teks-nya yang salah, apalagi jika kita meyakini bahwa itu adalah Kalam Ilahi Yang Maha Benar. Tetapi lebih sering karena mereka yang membacanya (dan yang mengaku pandai membacanya) terlalu terlenakan oleh "kebenaran instan" yang dirasa tak perlu lagi dipertanyakan atau diperdebatkan. Prosesi telah selesai, kebenaran telah menjadi. Tak diperlukan lagi perjalanan memunguti remah-remah hikmah dilakukan. Dan dengan begitu...merekapun menjadi buta, tuli dan bisu akan esensi dari luasnya hikmah dan indahnya kristal mutiara yang bertaburan di balik deretan huruf dan kata-kata !
Mereka tak lebih baik dari para penyembah api...
Medistra, Nisfu Sya'ban
..
Jumat
the Body is vanishing, but the Self is not
Bagi manusia, kematian adalah suatu momen yang bersifat pasti dan tak terelakkan. Pada saat itu segala apa yang telah diusahakan, yang sedang dilakukan dan yang direncanakan, seketika dihentikan secara paksa oleh kematian yang datang dengan tiba-tiba. Dalam kata-kata Martin Heidegger (1889-1976), seorang filsuf Jerman, kematian adalah “berakhirnya kemungkinan” atau “ketidakmungkinan dari kemungkinan”. Dan baginya kematian merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur ontologis eksistensi manusia, sehingga dapatlah dikatakan bahwa eksistensi manusia adalah “ada-menuju-kematian” (Sein-zum-Tode).
Dihadapkan pada kenyataan pasti datangnya kematian tersebut, seseorang bisa memilih bagaimana mensikapinya. Ia bisa meratapi hidupnya yang menjadi terbatas dan menjalaninya dalam kecemasan, ketakutan dan frustasi. Sebagian orang mencoba menggugat kenyataan dengan mengatakan bahwa kematian menyebabkan kebebasan manusia menjadi absurd, sebagaimana diungkapkan oleh A. Camus (1913-1960), yang kemudian melahirkan rasa ketidakberartian dalam hidup. Atau ia bisa menerimanya dengan sadar, untuk kemudian menjalani “jatah” umurnya dengan menghayati hidupnya dan mencoba memberinya makna, baik bagi dirinya maupun bagi yang lain di sekitarnya sebagaimana ditawarkan oleh T.G. Dobzhansky (1900-1975). Yang manapun yang ia pilih, yang pasti kematian akan tetap menjemputnya.
Lantas apakah sesudah mati manusia akan lenyap? Berbagai pemikiran filsafat telah menunjukkan bahwa manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, bahwa manusia adalah “roh-yang-bertubuh”. Manusia tidak dibangun hanya dari tubuh fisiologis, sehingga manusia bukanlah proses alamiah semata. Manusia adalah puncak dari seluruh proses evolusi kosmos, sebagaimana diuraikan oleh Teilhard de Chardin (1881-1955), dimana pada manusia tercapai titik tertinggi dari ekspresi energi positif dan kesadaran semesta.
Seluruh pengalaman refleksi, pengalaman antar subyektif, pengalaman akan nilai-nilai kebenaran, pengalaman kebebasan, pengalaman transendensi dalam berbagai aspek kehidupan, terakumulasi sepanjang proses “menjadi”-nya dan terekam dalam dimensi kesadaran manusia yang metahistoris dan abadi. Dengan ciri temporalitasnya, manusia pun memiliki kemampuan untuk “melepaskan diri” dari penjara waktu dan “hidup abadi” dengan cara mentransendir kekiniannya menjadi sebuah eksistensi yang otentik. Meninggalkan legacy, menjadi tokoh dan menyejarah. Sejatinya, manusia memiliki dimensi kesadaran yang akan terus ada bahkan setelah kematian tubuh kasarnya. The body is vanishing, but” the Self” is not.
In memoriam of my father, MDP, a truly fighter
31 July 1942~ 13 July 2008
..
Dihadapkan pada kenyataan pasti datangnya kematian tersebut, seseorang bisa memilih bagaimana mensikapinya. Ia bisa meratapi hidupnya yang menjadi terbatas dan menjalaninya dalam kecemasan, ketakutan dan frustasi. Sebagian orang mencoba menggugat kenyataan dengan mengatakan bahwa kematian menyebabkan kebebasan manusia menjadi absurd, sebagaimana diungkapkan oleh A. Camus (1913-1960), yang kemudian melahirkan rasa ketidakberartian dalam hidup. Atau ia bisa menerimanya dengan sadar, untuk kemudian menjalani “jatah” umurnya dengan menghayati hidupnya dan mencoba memberinya makna, baik bagi dirinya maupun bagi yang lain di sekitarnya sebagaimana ditawarkan oleh T.G. Dobzhansky (1900-1975). Yang manapun yang ia pilih, yang pasti kematian akan tetap menjemputnya.
Lantas apakah sesudah mati manusia akan lenyap? Berbagai pemikiran filsafat telah menunjukkan bahwa manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, bahwa manusia adalah “roh-yang-bertubuh”. Manusia tidak dibangun hanya dari tubuh fisiologis, sehingga manusia bukanlah proses alamiah semata. Manusia adalah puncak dari seluruh proses evolusi kosmos, sebagaimana diuraikan oleh Teilhard de Chardin (1881-1955), dimana pada manusia tercapai titik tertinggi dari ekspresi energi positif dan kesadaran semesta.
Seluruh pengalaman refleksi, pengalaman antar subyektif, pengalaman akan nilai-nilai kebenaran, pengalaman kebebasan, pengalaman transendensi dalam berbagai aspek kehidupan, terakumulasi sepanjang proses “menjadi”-nya dan terekam dalam dimensi kesadaran manusia yang metahistoris dan abadi. Dengan ciri temporalitasnya, manusia pun memiliki kemampuan untuk “melepaskan diri” dari penjara waktu dan “hidup abadi” dengan cara mentransendir kekiniannya menjadi sebuah eksistensi yang otentik. Meninggalkan legacy, menjadi tokoh dan menyejarah. Sejatinya, manusia memiliki dimensi kesadaran yang akan terus ada bahkan setelah kematian tubuh kasarnya. The body is vanishing, but” the Self” is not.
In memoriam of my father, MDP, a truly fighter
31 July 1942~ 13 July 2008
..
Tuhan Yang Terasing dan Agama Manusia-Manusia
Tak perlu malu untuk mengakui bahwa dihadapkan pada perubahan layar peradaban, agama-agama menjadi tergagap akan peran seperti apa yang harus dimainkannya? Ketika layar semakin diwarnai oleh pertautan warna-warna budaya yang lebih beragam, yang masing-masingnya memberi keindahan...tak lagi mudah untuk menyebut satu warna saja sebagai warna yang paling betul. Semuanya berkelindan satu sama lain, apakah pada persentuhan, persilangan maupun dalam percampuran. Ketika langgam globalisasi yang dimainkan menjadi lebih menyeragam di penjuru bentangan layar, maka penghayatan kehidupan dan penghayatan ketuhanan justru menjadi semakin individualis -atau bahkan narsistis-. Dalam interaksi yang semakin tak berbatas di antara mereka, manusia-manusia semakin sadar akan segenap potensi dirinya dan kemampuan eksplorasi nalarnya. Dalam kondisi seperti itu, maka setiap upaya penyeragaman nilai-nilai moral (sebagai hasil rumusan interpretasi subyektif dari sebagian mereka yang merasa memiliki otoritas moral) senantiasa dihadapkan kepada interpretasi-interpretasi subyektif lain yang berbeda (bahkan bertentangan). Pemaksaan interpretasi tunggal sebagai sebuah kebenaran mutlak menjadi semakin sulit dilakukan akhir-akhir ini :)..
Dan ketika para penafsir kata-kata Tuhan kemudian mengambil sikap apriori terhadap arus perubahan ini, dengan justru semakin membangun tembok-tembok tinggi -demi membela kemuliaan Tuhan-, maka agama-agama semakin kehilangan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Di waktu-waktu ritual, agama seakan menguasai para penganutnya. Mendera mereka dengan hujatan-hujatan terhadap arus modernitas dan keberagaman. Mengingatkan akan ketidakmampuan nalar manusia berhadapan dengan keMaha Sempurnaan dan ke Mahapengetahuan Tuhan. Tak ada lagi yang perlu diperdebatkan ataupun diperbaiki dari ajaran-ajaranNya! Di waktu-waktu hari raya keagamaan, agama seakan meraja. Namun di waktu-waktu lainnya, agama tak pernah diinginkan hadir karena tak terlihat memberikan apa-apa yang bermanfaat bagi kemajuan. Di ruang-ruang peribadatan, semua kepala tunduk mendengarkan "kebenaran" ini dan "kebenaran" itu, "itu tidak benar", "ini paling benar". Namun segala hukum dan fatwa semakin tak pernah masuk lebih jauh dari gendang telinga. Meminjam terminologi ilmu ekonomi, terjadi fenomena decoupling antara ajaran dan realita.
Ajaran semakin (dirasa) tak relevan diterapkan dalam realita. Tuhan seakan tak lagi hadir memberi jalan keluar bagi kemiskinan, penderitaan, perang dan genocide. Fatwa, yang mengklaim dirinya sebagai "kata-kata Tuhan" semakin menjauh dari kenyataan hidup yang dihadapi oleh manusia modern, sehingga kehilangan wibawanya. Atau malah semakin diabaikan dengan diam-diam, tanpa harus merasa bersalah dan berdosa.
Ketika fatwa dirumuskan secara "gampangan" dan soo far away dari kenyataan kehidupan yang dihadapi sehari-hari....ketika agama menjadi semata lembaga kumpulan "koleksi kebenaran" yang beku, tak mau mendengarkan dan tak mau tahu....maka semakin hari agama akan semakin kehilangan relevansinya sebagai sebuah pedoman apalagi penuntun hidup manusia modern. Agama yang tak bersedia berubah...cuma akan menjadi "agama-nya Tuhan", tetapi ia berhenti menjadi agama-nya manusia-manusia.
Tak heran jika kegemasan akan irelevansi "agama Tuhan" dengan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh manusia modern tersebut sempat memuncak di tahun 60-an, dengan lahirnya sebuah gerakan pemikiran berlabel "God is dead theology"! Bahkan majalah terkemuka dunia, TIME, pada saat itu (edisi 22 Oktober 1965) menampilkan sebagai sampul mukanya secara sangat mencolok dalam huruf kapital..."Is God Dead?".... ( http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,941410-1,00.html )
Tentu saja, statement itu tidak boleh dimaknai secara harfiah begitu saja. Gerakan tersebut sama sekali tidak bertujuan untuk menolak Tuhan (ataupun "mematikan" Tuhan secara fisikal) dan menggantinya dengan manusia sebagai Ilah baru. Bukan. Yang mereka perjuangkan, adalah mengembangkan paham ketuhanan dalam tataran dunia manusia.
"Tuhan yang asing" dari permasalahan manusia "dimatikan", dan digantikan dengan "Tuhan yang hidup bersama manusia" dan secara bersama-sama merasakan segala penderitaan manusia dan ikut berpartisipasi menyembuhkannya.
..
Dan ketika para penafsir kata-kata Tuhan kemudian mengambil sikap apriori terhadap arus perubahan ini, dengan justru semakin membangun tembok-tembok tinggi -demi membela kemuliaan Tuhan-, maka agama-agama semakin kehilangan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Di waktu-waktu ritual, agama seakan menguasai para penganutnya. Mendera mereka dengan hujatan-hujatan terhadap arus modernitas dan keberagaman. Mengingatkan akan ketidakmampuan nalar manusia berhadapan dengan keMaha Sempurnaan dan ke Mahapengetahuan Tuhan. Tak ada lagi yang perlu diperdebatkan ataupun diperbaiki dari ajaran-ajaranNya! Di waktu-waktu hari raya keagamaan, agama seakan meraja. Namun di waktu-waktu lainnya, agama tak pernah diinginkan hadir karena tak terlihat memberikan apa-apa yang bermanfaat bagi kemajuan. Di ruang-ruang peribadatan, semua kepala tunduk mendengarkan "kebenaran" ini dan "kebenaran" itu, "itu tidak benar", "ini paling benar". Namun segala hukum dan fatwa semakin tak pernah masuk lebih jauh dari gendang telinga. Meminjam terminologi ilmu ekonomi, terjadi fenomena decoupling antara ajaran dan realita.
Ajaran semakin (dirasa) tak relevan diterapkan dalam realita. Tuhan seakan tak lagi hadir memberi jalan keluar bagi kemiskinan, penderitaan, perang dan genocide. Fatwa, yang mengklaim dirinya sebagai "kata-kata Tuhan" semakin menjauh dari kenyataan hidup yang dihadapi oleh manusia modern, sehingga kehilangan wibawanya. Atau malah semakin diabaikan dengan diam-diam, tanpa harus merasa bersalah dan berdosa.
Ketika fatwa dirumuskan secara "gampangan" dan soo far away dari kenyataan kehidupan yang dihadapi sehari-hari....ketika agama menjadi semata lembaga kumpulan "koleksi kebenaran" yang beku, tak mau mendengarkan dan tak mau tahu....maka semakin hari agama akan semakin kehilangan relevansinya sebagai sebuah pedoman apalagi penuntun hidup manusia modern. Agama yang tak bersedia berubah...cuma akan menjadi "agama-nya Tuhan", tetapi ia berhenti menjadi agama-nya manusia-manusia.
Tak heran jika kegemasan akan irelevansi "agama Tuhan" dengan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh manusia modern tersebut sempat memuncak di tahun 60-an, dengan lahirnya sebuah gerakan pemikiran berlabel "God is dead theology"! Bahkan majalah terkemuka dunia, TIME, pada saat itu (edisi 22 Oktober 1965) menampilkan sebagai sampul mukanya secara sangat mencolok dalam huruf kapital..."Is God Dead?".... ( http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,941410-1,00.html )
Tentu saja, statement itu tidak boleh dimaknai secara harfiah begitu saja. Gerakan tersebut sama sekali tidak bertujuan untuk menolak Tuhan (ataupun "mematikan" Tuhan secara fisikal) dan menggantinya dengan manusia sebagai Ilah baru. Bukan. Yang mereka perjuangkan, adalah mengembangkan paham ketuhanan dalam tataran dunia manusia.
"Tuhan yang asing" dari permasalahan manusia "dimatikan", dan digantikan dengan "Tuhan yang hidup bersama manusia" dan secara bersama-sama merasakan segala penderitaan manusia dan ikut berpartisipasi menyembuhkannya.
..
Langganan:
Postingan (Atom)