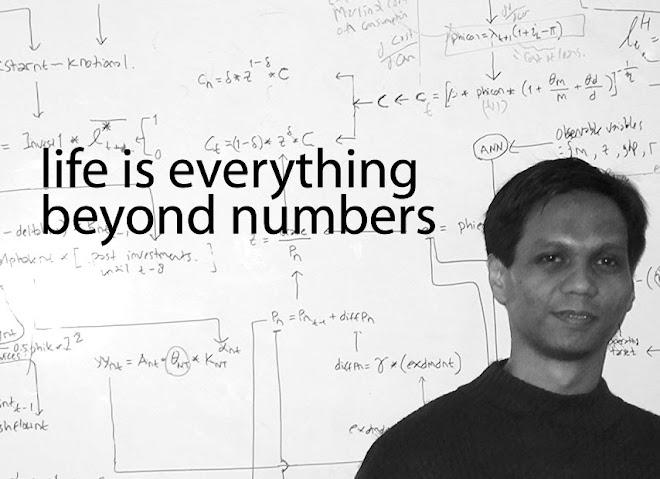Minggu
Ruang Bagi Orang Lain (yang berbeda)
Perhatikan ketika kita berbicara dengan diri sendiri. Kita dapat mendengar diri kita sendiri berbicara, hanya jika terjadi break-point yang membedakan saya sebagai pembicara dan saya sebagai pendengar...terjadinya difference yang membedakan antara saya dengan diri saya...terjadinya spacing (espacement) yang memungkinkan saya sekaligus mendengar apa yang saya katakan...terjadinya ruang antara di mana the trace (bangkitan memori masa lalu) terbentuk...dan terbentuknya ruang antara dimana terjadi repetisi masa lalu ke masa kini.
Dan Jacques Derrida (1930-2004), seorang filsuf kelahiran Algeria, menunjukkan, bahwa pada setiap pengalaman, spacing (espacement) pasti terjadi. Bahkan pada pengalaman yang hanya melibatkan diri sendiri (auto-affection) semisal bercermin atau berbisik kepada diri sendiri. Senantiasa ada ruang yang membedakan antara aku (me) dengan aku yang lain di dalam diri ku (an other in me).
Jika dengan diri sendiri saja kita tak pernah bisa menyatu, senantiasa ada ruang terbuka...seyogianya kita bisa membuka ruang itu bagi orang lain di luar diri kita!
“...that the identitiy in the case of cultures, persons, nations, languages is a set different item, it is identity as differance from itself, that is, within an opening within itself, a gap within itself. That's not only a fact, a structure, but it's a duty, it's an ethical and political duty to take into account this impossibility of unifying, of being one with oneself.”
Dan dalam kondisi demikianlah maka kita seyogianya menjadi sadar diri, bahwa kita tak pernah bisa berbicara mengatasnamakan orang lain alih-alih menggurui atau bahkan menguasai orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah membuka diri bagi orang lain, membuka ruang antara di dalam diri kita untuk juga menerima identitas orang banyak yang lain di luar kita (plus d’un).
Hanya dengan kesadaran yang demikianlah, yang disertai dengan kerendah hatian, maka manusia dapat menerima manusia lain dan identitas lain hadir dalam dunianya. Untuk mecapai harmoni, seyogianya dihindarkan upaya untuk membentuk keseragaman (unity) mutlak. Justru dengan menghargai perbedaan, keterpisahan (separation, dissociation), kita akan dapat melihat orang lain sebagai orang lain yang sederajat dan kita tidak akan mencoba menggantikan eksistensinya dengan eksistensi dan kehendak kita.
.
Aku dan Anda berbeda, dan biarlah demikian...
Mengingat kembali, bahwa ketelanjangan wajah (epifani) adalah kehadiran langsung dari “yang lain” sebagai “yang lain” (Emmanuel Levinas, 1906-1995). Antarsubyektivitas adalah perjumpaan antara Aku sebagai manusia yang otentik menjadi Aku....dengan yang lain, yang juga secara otentik menjadi yang lain. Anda adalah misteri yang tak pernah merupakan pengalaman ilmiah. Tak ada orang yang bisa memaksa anda menjadi seseorang atau sesuatu yang lain. Tak ada orang yang bisa “menggunakan” Anda. Anda tak pernah merupakan “obyek”. Maka dalam hubungan Aku-Anda tak pernah ada hubungan penguasaan dari Aku terhadap Anda atau Anda terhadap Aku.
Seorang filsuf Austria, Martin Buber (1878-1965), menyatakan bahwa hubungan antarpersonal seyogianya bersifat mutual dan holistik, dimana hubungan “Aku-Anda” (Ich-Du, I-Thou) adalah hubungan dua kutub yang setara, yang merupakan hubungan timbal balik yang sempurna (Gegenseitigkeit). Lebih jauh Gabriel Madinier (1895-1958) mengatakan, bahwa “menghendaki yang lain sebagai subyek” merupakan cerminan cinta kasih. Dan dalam cinta kasih kita tidak ingin “menguasai” atau “memiliki” orang lain, baik secara fisik, psikis maupun intelektual. Cinta yang murni adalah cinta yang tidak bersyarat, dan yang hanya menginginkan kebaikan dari yang dicintai; velle alicui bonum (Thomas Aquinas, 1225-1274).
Dengan demikian, secara umum antarsubyektivitas mengingatkan sebuah visi kemanusiaan yang memandang “yang lain” (manusia lain dan lingkungan) sebagai yang setara, yang harus diperlakukan dengan rasa cintakasih, berkeadilan dan empati. Tidak boleh ada pemaksaan terhadap yang lain untuk merubah dirinya menjadi Aku. Anda adalah anda yang otentik, dan Aku tak pernah boleh merubah Anda menjadi Aku !!...
.
Itu kan Kebenaran Versi Anda ?!
To them, I said, the truth would be literally nothing but the shadows of the images
(Plato, “Politeia”)
Inilah zaman di mana kata “kebenaran” seringkali menjadi kata pamungkas untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan perseorangan maupun kelompok. Dunia dipenuhi oleh beragam mereka yang meng-klaim dirinya sebagai pemilik kebenaran, yang saling berlomba untuk bisa mendominasi tatanan pemikiran, prinsip serta norma. Pencapaian hegemoni lalu dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan tak jarang pula dengan penindasan bahkan pemusnahan atas orang lain yang tidak sepaham. Bagi mereka, kebenaran hanyalah apa yang ada di dalam kepala mereka. Apa yang baik dan apa yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak patut dilakukan, bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah, semuanya haruslah berdasarkan standar “kebenaran” yang mereka sendiri tetapkan. Kata “kebenaran” mereka jadikan tuhan yang tidak boleh digugat dan dipertanyakan. Dalam kondisi demikian, maka norma sebagai landasan perilaku individu dan sebagai basis sosial masyarakat hanyalah kata lain dari “dinding penjara” dan hukum sebagai acuan benar-salah hanyalah kata lain dari “tangan-tangan penguasa”.
Sesugguhnyalah kita tidak pernah mampu untuk memahami secara utuh tentang segala sesuatu. Kita tidak “memiliki” kebenaran. Sehingga tak seorangpun bisa mengklaim bahwa dirinya atau kelompoknya adalah pemegang kunci-kunci kebenaran sejati. Tugas kita, hanyalah untuk terus membuka diri seluasnya dan terus mencari hikmat dan kebenaran sejati di balik beragam bayang-bayang interpretasi manusia tentang kebenaran. Dalam dunia bayang-bayang yang dibangun oleh interpretasi dan abstraksi inilah kita ditunut untuk melakukan refleksi.
Pertama, refleksi tentang batas-batas kemampuan pengetahuan kita dan kemampuan-kemampuan kita terhadap kebaikan maupun kejahatan. Sebagaimana disimpulkan oleh Karl Popper dalam kata-katanya yang terkenal: “Our knowledge can only be finite, while our ignorance must necessarily be infinite.” (Karl Popper, Conjectures and Refutations, 1963).
Kedua, refleksi tentang keterbatasan ilmu serta pemahaman -yang terlahir dari keterbatasan kemampuan pengetahuan kita tersebut- yang tak mampu mencapai suatu gambaran yang menyeluruh tentang fenomena. Sebagaimana disimpulkan oleh Alfred North Whitehead, "There are no whole truths; all truths are half-truths. It is trying to treat them as whole truths that plays the devil". (Dialogues of Alfred North Whitehead, 1954).
Terhadap semua pendapat, presuposisi dan interpretasi yang diajukan oleh pemikiran manusia tentang realitas, kita dituntut untuk “membedahnya” dengan pisau sistematika berfikir yang kritis dan menyeluruh untuk mendapatkan makna dan fondasi paling mendasarnya. Kita dituntut untuk mampu memisahkan antara pengetahuan semu dengan pengetahuan sejati yang sungguh-sungguh mencerminkan kebenaran. Memisahkan antara “kebenaran” yang dibangun dari bayang-bayang (becoming, doxa) dengan hikmat dari kebenaran yang sesungguhnya (being, episteme).
.