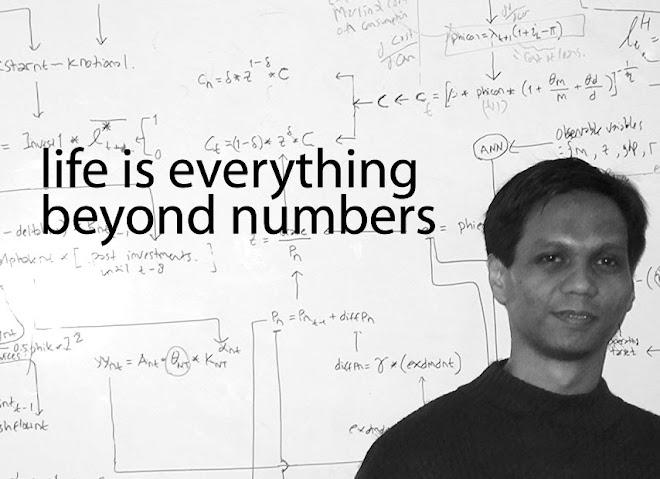Seratus tahun sebelum hari ini, dan selama tujuh puluh tahun sebelumnya lagi, apa yang negeri ini miliki? Rakyat yang buta huruf, tertindas, dan tiada memiliki keinginan ataupun mimpi saking miskinnya ia. Di Pulau Jawa, rata-rata dari 1000 orang hanya 15 org saja yang bisa baca tulis. Bila perempuan ikut dihitung, jumlahnya menjadi 16 saja. Di daerah Madiun, dari 1000 orang hanya 24 orang yang tidak buta huruf. Di Jakarta hanya 9 orang, di daerah sekitar Jakarta hanya 5 orang, di daerah Madura 6 orang, di daerah Tangerang, Jatinegara, dan Karawang masing-masing 1 orang. (Mahlenfeld, de Locomotief).
Tahun baru 1830, sepertinya menjadi awal dimulainya sebuah peradaban air mata di negeri ini. Dengan semangat baru setelah memenangkan Perang Jawa, kini agenda baru pemerintah kolonial adalah untuk menggenjot devisa bagi negeri tanah rendahnya. Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru, Johannes van Den Bosch tiba di Batavia pada bulan Januari 1830…dengan membawa sistem produksi massal yang juga baru: cultuurstelsel.
Van Den Bosch percaya, bahwa petani penduduk negeri kepulauan ini tidak memiliki pengetahuan dan kemauan yang cukup untuk memajukan dirinya sendiri. Mereka harus dibimbing oleh penguasa, harus diajar untuk bekerja, dan kalau perlu dipaksa untuk bekerja! Keyakinannya ini sangat bertolak belakang dengan pandangan liberal Muntinghe, “Biarkan petani Jawa bebas menangani urusannya sendiri…dan ia akan menghiasi perbukitan dengan sawah-sawahnya..”. Van Den Bosch tidak percaya itu. Rakyat malang negeri ini, yakin ia, hanya bisa bekerja jika dipaksa utk mau bekerja.
Maka sejak itu dimulailah eksploitasi kolonialis secara lebih menggila. Tujuh puluh persen keluarga petani dipaksa untuk menanami tanahnya dengan komoditi ekspor kopi, tebu dan nila. Bahkan di beberapa daerah seperti Banten, Banyumas dan Kedu, seluruh keluarga petani menjadi alat produksi bagi sistem produksi massal ini. Produksi komoditas ekspor terbukti meningkat pesat berlipat-lipat.
Apa yang diperoleh Belanda dari cultuurstelsel? Uang dalam jumlah yang besar dikirim ke negeri Belanda. Dari tahun 1831-1877, perbendaharaan negeri Belanda menerima 832 juta florins. Sebelum tahun 1850, kiriman uang tersebut mengisi sekitar 19% dari pendapatan negara Belanda. Lalu menjadi sekitar 32% pada tahun 1851-1860, dan menjadi sekitar 34% pada tahun 1860-1866. Pendapatan ini yang membuat perekonomian dalam negeri Belanda stabil: hutang-hutang dilunasi, pajak diturunkan, kanal dan terusan serta jalan kereta api negara dibangun. Semuanya dari keuntungan-keuntungan yang diperas dari desa-desa di Jawa. Pada periode “liberal” selanjutnya (1870-1900), swasta menggantikan peran pemerintah kolonial. Jumlah orang sipil Eropa di Jawa meningkat dengan pesat, dari 17.285 orang pada tahun 1852 menjadi 62.477 orang pada tahun 1900. Sejumlah bank swasta mulai berdiri, misalnya: Bank Dagang Hindia Belanda (yang paling utama), Koloniale Bank, Handelsvereeniging Amsterdam, Dorrepaal & Co, Vorstenlanden. Dan nusantara memasuki zaman puncak eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian Jawa maupun daerah-daerah di luar Jawa.
Apa yang diperoleh rakyat biasa pribumi nusantara? Di depan mata Wahidin Sudirohusodo dan segelintir kaum muda perhimpunan Budi Utomo, yang terhampar hanya penderitaan dan air mata. Rakyat yang tidak berani untuk memiliki cita-cita bahkan putus asa untuk berharap. Mereka hanya (boleh) punya dengkul untuk menyangga tubuhnya mencangkul di tanah-tanah penanaman. Mereka tak punya siapa-siapa untuk mengadukan duka. Saudara sebangsa yang berpangkat, para pangreh praja, tak bisa diharapkan karena telah menjadi bawahan kolonial yang taat dan turut serta melakukan penghisapan terhadap rakyat.
Itulah nasib negeri yang harus dibebaskan, yang semangat pembebasannya telah digelorakan oleh seorang pensiunan dokter Jawa Wahidin dari kota ke kota. Dan segelintir kaum muda perhimpunan Budi Utomo pada seratus tahun yang lalu…
Tahun baru 1830, sepertinya menjadi awal dimulainya sebuah peradaban air mata di negeri ini. Dengan semangat baru setelah memenangkan Perang Jawa, kini agenda baru pemerintah kolonial adalah untuk menggenjot devisa bagi negeri tanah rendahnya. Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru, Johannes van Den Bosch tiba di Batavia pada bulan Januari 1830…dengan membawa sistem produksi massal yang juga baru: cultuurstelsel.
Van Den Bosch percaya, bahwa petani penduduk negeri kepulauan ini tidak memiliki pengetahuan dan kemauan yang cukup untuk memajukan dirinya sendiri. Mereka harus dibimbing oleh penguasa, harus diajar untuk bekerja, dan kalau perlu dipaksa untuk bekerja! Keyakinannya ini sangat bertolak belakang dengan pandangan liberal Muntinghe, “Biarkan petani Jawa bebas menangani urusannya sendiri…dan ia akan menghiasi perbukitan dengan sawah-sawahnya..”. Van Den Bosch tidak percaya itu. Rakyat malang negeri ini, yakin ia, hanya bisa bekerja jika dipaksa utk mau bekerja.
Maka sejak itu dimulailah eksploitasi kolonialis secara lebih menggila. Tujuh puluh persen keluarga petani dipaksa untuk menanami tanahnya dengan komoditi ekspor kopi, tebu dan nila. Bahkan di beberapa daerah seperti Banten, Banyumas dan Kedu, seluruh keluarga petani menjadi alat produksi bagi sistem produksi massal ini. Produksi komoditas ekspor terbukti meningkat pesat berlipat-lipat.
Apa yang diperoleh Belanda dari cultuurstelsel? Uang dalam jumlah yang besar dikirim ke negeri Belanda. Dari tahun 1831-1877, perbendaharaan negeri Belanda menerima 832 juta florins. Sebelum tahun 1850, kiriman uang tersebut mengisi sekitar 19% dari pendapatan negara Belanda. Lalu menjadi sekitar 32% pada tahun 1851-1860, dan menjadi sekitar 34% pada tahun 1860-1866. Pendapatan ini yang membuat perekonomian dalam negeri Belanda stabil: hutang-hutang dilunasi, pajak diturunkan, kanal dan terusan serta jalan kereta api negara dibangun. Semuanya dari keuntungan-keuntungan yang diperas dari desa-desa di Jawa. Pada periode “liberal” selanjutnya (1870-1900), swasta menggantikan peran pemerintah kolonial. Jumlah orang sipil Eropa di Jawa meningkat dengan pesat, dari 17.285 orang pada tahun 1852 menjadi 62.477 orang pada tahun 1900. Sejumlah bank swasta mulai berdiri, misalnya: Bank Dagang Hindia Belanda (yang paling utama), Koloniale Bank, Handelsvereeniging Amsterdam, Dorrepaal & Co, Vorstenlanden. Dan nusantara memasuki zaman puncak eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian Jawa maupun daerah-daerah di luar Jawa.
Apa yang diperoleh rakyat biasa pribumi nusantara? Di depan mata Wahidin Sudirohusodo dan segelintir kaum muda perhimpunan Budi Utomo, yang terhampar hanya penderitaan dan air mata. Rakyat yang tidak berani untuk memiliki cita-cita bahkan putus asa untuk berharap. Mereka hanya (boleh) punya dengkul untuk menyangga tubuhnya mencangkul di tanah-tanah penanaman. Mereka tak punya siapa-siapa untuk mengadukan duka. Saudara sebangsa yang berpangkat, para pangreh praja, tak bisa diharapkan karena telah menjadi bawahan kolonial yang taat dan turut serta melakukan penghisapan terhadap rakyat.
Itulah nasib negeri yang harus dibebaskan, yang semangat pembebasannya telah digelorakan oleh seorang pensiunan dokter Jawa Wahidin dari kota ke kota. Dan segelintir kaum muda perhimpunan Budi Utomo pada seratus tahun yang lalu…
Oktober 2008