
Ribuan tahun telah berlalu, dan sedemikian lamanya pula peradaban manusia telah dibangun di atas fondasi yang sangat rapuh: ego, dengan mana ia diciptakan. Peradaban demi peradaban dibangun dan runtuh silih berganti, hanya untuk menunjukkan bahwa sepanjang sejarahnya manusia tak kunjung bisa menaklukkan egonya. Setiap peradaban senantiasa diwarnai oleh perbenturan dan tarik-menarik antara berbagai ego yang masing-masing menuntut kebesaran diri, penguasaan sebesar-besarnya atas pihak lain, pemenuhan kepuasan diri sendiri, maupun ketamakan serta kerakusan (yg merupakan paradoks terhadap tujuan bersama untuk menggapai kemakmuran dan kesejahteraan).
Dan kehadiran uang, apapun nama dan bentuknya: cangkang kerang, gigi unta, gading gajah, cula badak, kulit sapi, domba, tembakau, batuan mineral semisal amber, dinar emas dan perak, kertas, kartu plastik, atau bahkan sekedar angka-angka dalam buku tabungan, menjanjikan semua yang ego butuhkan. Kepemilikan uang (apakah itu dlm wujud gigi unta, kertas, emas ataupun perak) tidak hanya menjanjikan kemampuan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan sehari-hari, tapi lebih dari itu; ia menjanjikan kemampuan untuk mewujudkan hasrat manusia untuk hidup abadi melalui penumpukan harta warisan. Ia menjanjikan kemampuan menaklukkan masa depan melalui penumpukan uang dan pemastian aliran future income.
Cangkang kerang, gigi unta ataupun secarik kertas pada hakekatnya tidaklah berharga, kecuali jika kemudian semua orang mempercayainya sebagai sesuatu yang berharga (shared & agreed values). Seorang pembeli tidak mungkin bisa menukarkan cangkang kerang dengan barang yang dibutuhkannya, apabila si penjual tidak percaya bahwa cangkang kerang itu berharga. Demikian pula, pegawai kantoran tidak akan mau bekerja kecuali jika secarik kertas yang ia terima di akhir bulan dipercayainya berharga untuk nanti ditukar dengan makanan dan pakaian. Supermarket akan memberi makanan dan pakaian dengan kepercayaan bahwa secarik kertas itu dapat ia bawa ke bank dan menambah jumlah kekayaannya. Demikianlah maka mata rantai “money illusion” ini pada akhirnya membentuk sebuah system of belief tentang berharganya secarik kertas atau cangkang kerang atau gigi unta tersebut. Manusia kemudian bersama-sama tersihir oleh ilusi yang berasal dari benda-benda, sehingga kita sangat percaya bahwa benda-benda itu memiliki nilai dan kekuatan yang jauh lebih besar daripada penampakan biasanya.
Irasional? Ya. Sama irasionalnya dengan “nilai” yang kita sematkan kepada sekeping kartu debet plastik, secarik uang kertas dollar atau rupiah (fiat/representative money), maupun dinar emas (commodity money). Tak peduli apapun bentuknya!
Dan ketika kekuatan psikologis akhirnya juga kita serahkan kepada benda-benda yang kita sebut sebagai “uang”, maka money illusion menjanjikan kekuataan yang lebih besar lagi: penguasaan atas uang (dan sumber-sumber ekonomi) menjanjikan kendali kekuasaan atas orang lain dan bahkan atas sebuah negeri. Kepemilikan uang sebanyak-banyaknya menjanjikan kemampuan untuk mewujudkan semua keinginan dan mimpi-mimpi dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup! Conspicuous consumption, reputable wastefulness and futility adalah kata lain dari konsumerisme pada abad ke-19 (Thorstein Veblen (1981), The Theory of the Leisure Class). Dan dalam jebakan ilusi, manusia menjadi semakin kerasukan mengejar materi. Sebagaimana Midas sang raja, untuk setiap benda yang disentuhnya menjadi emas maka satu kehausan muncul untuk menyentuh benda lainnya. Satu kehausan melahirkan kehausan berikutnya. Demikian seterusnya hingga puteri kesayangannya pun menjadi emas membatu.
Peradaban-peradaban awal manusia sebenarnya sangat menyadari tentang betapa dahsyatnya kekuatan ilusi yang dikandung oleh uang (apapun bentuknya) dalam merayu ego manusia. Dan mereka berusaha memberi kekuatan kepada manusia untuk tidak terjebak ke dalamnya, dengan menanamkan kesadaran bhw uang adalah sesuatu yang sakral yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan penggunaannya kpd para Dewa di atas mereka. Penerbitan uang pertama bangsa Romawi, misalnya, diawali dgn prosesi “pensucian” di kuil dewi Juno dan pemberian nama mata uang yang bernuansa religius: “moneta” yang juga merupakan sebutan bagi dewi Juno. Demikian pula dengan bangsa-bangsa sebelumnya (Yunani, Babilonia dan Mesir) yang juga senantiasa menyematkan nuansa religi pada mata uangnya; penggunaan emas dan perak sebagai uang diyakini merupakan simbol dari korelasi mistis antara Matahari dan Bulan.
Dan semakin “berkuasanya” uang dalam kehidupan sehari-hari serta kehancuran sosio-ekonomi yang diakibatkannya, bahkan pada abad-abad awal lahirnya, memunculkan gambaran bahwa uang tidak lain adalah perwujudan lain dari iblis dan setan. Di masa peradaban Babilonia, kehadiran emas dikatakan sebagai “the excrement of Hell” (kotoran neraka). Sepanjang sejarahnya, manusia semakin keras berteriak tentang kehadiran Iblis dan setan yang menyertai kekuatan destruktif dari uang. Namun mereka sepertinya tak pernah sadar, bahwa Iblis dan setan itu adalah makhluk yang sama yang telah mereka lepaskan dari rantai kendali dari dalam diri mereka sendiri. Dan yang selama ini bahkan telah mereka besarkan dengan asupan ego mereka sendiri yang semakin besar dan semakin besar kekuatan kendalinya…
Ego, yang telah meruntuhkan mimpi John Maynard Keynes (1932) tujuh puluh lima tahun yang lalu tentang sebuah peradaban manusia yang seharusnya :
“…when the accumulation of wealth is no longer of high social importance, there will be great changes in the code of morals. We shall be able to rid ourselves of many of the pseudo-moral principles which have hag-ridden us for two hundred years, by which we have exalted some of the most distasteful of human qualities into position of the highest virtues. We shall be able to afford to dare to assess the money-motive at its true value. The love of money as a possesion –as distinguished from the love of money as a means to the enjoyments and realities of life – will be recognized for what it is, a somewhat disgusting morbidity, one of those semi-criminal, semi-pathological propensities…” (Economic Possibilities for Our Grandchildren, Essays in Persuasion, John Maynard Keynes, 1932)
...

























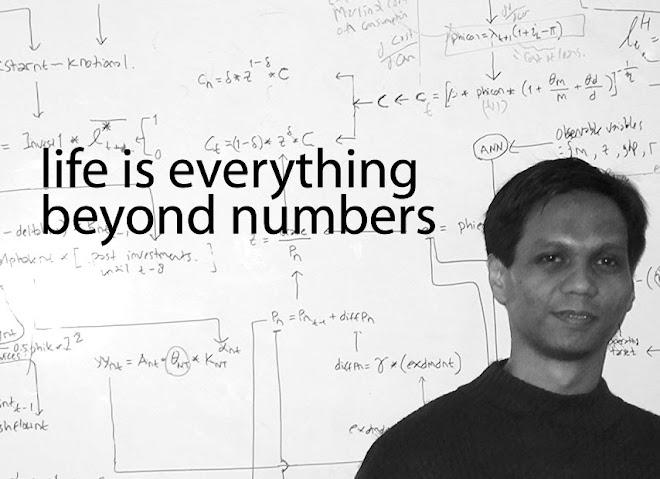
Tidak ada komentar:
Posting Komentar